1984 dan Brave New World
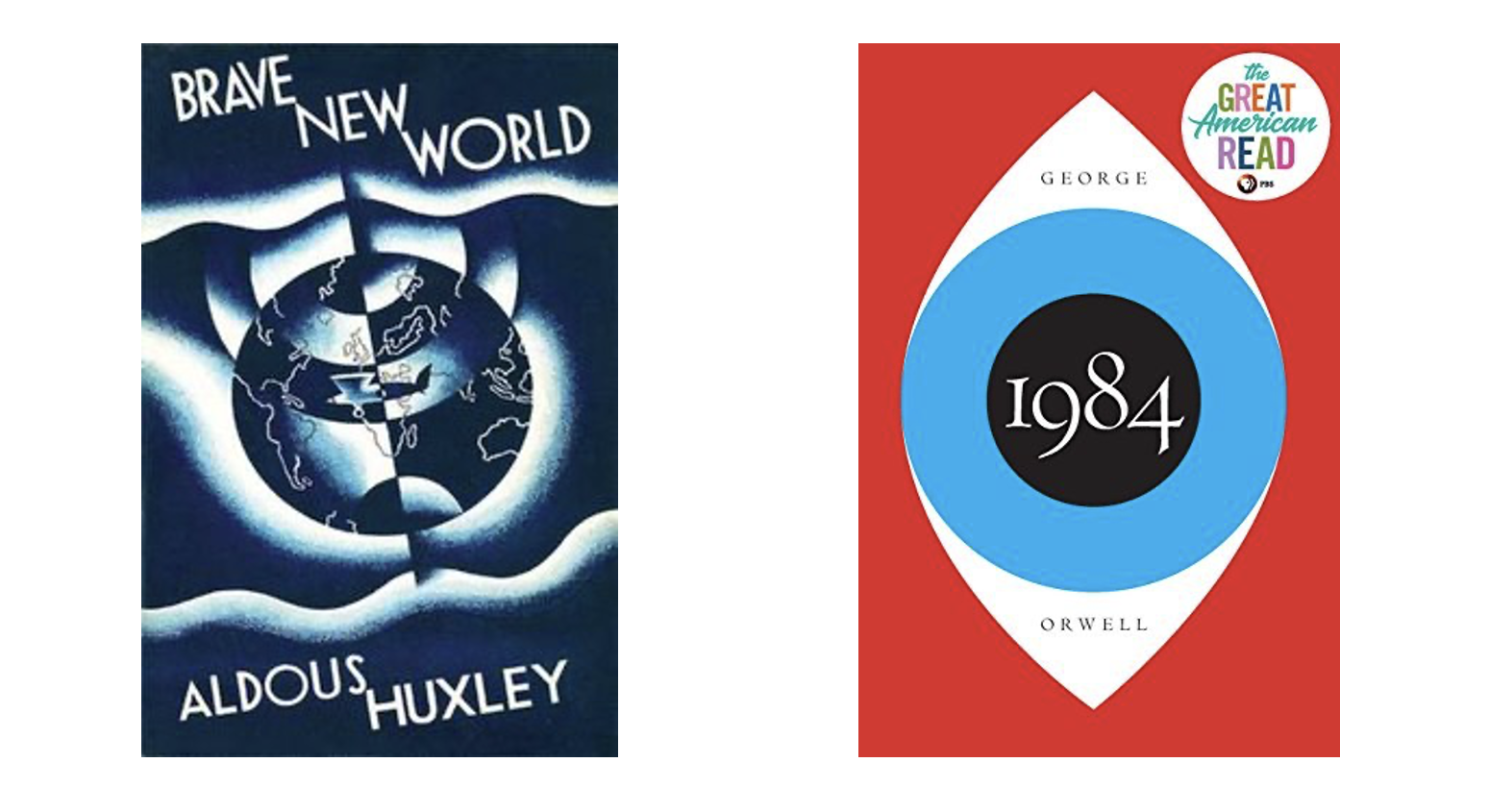
1984 karya George Orwell (1949) dan Brave New World karya Aldous Huxley (1932) mungkin dua novel dystopia paling berpengaruh di abad ke-20. Keduanya menggambarkan masa depan yang suram. Masyarakat dikendalikan oleh kekuasaan yang opresif, namun dengan cara yang sangat berbeda.
1984 berlatar di Oceania, sebuah negara totaliter yang dipimpin oleh partai dan sosok pemimpin yang disebut Big Brother. Novel ini menceritakan kekuasaan absolut yang dipertahankan melalui pengawasan ketat (seperti telescreen dan polisi pikiran), propaganda, serta penghapusan kebebasan berpikir. Pemerintah memanipulasi kenyataan dengan konsep doublethink (memercayai dua hal yang bertentangan) dan Newspeak (bahasa yang dirancang untuk membatasi pemikiran kritis). Tokoh utama, Winston Smith, memberontak tetapi akhirnya dihancurkan melalui penyiksaan dan cuci otak. Pesan Orwell jelas: tirani bisa muncul melalui kekerasan, pengawasan, dan penindasan kebebasan.
Sementara itu, Brave New World menggambarkan dunia dengan manusia yang dikendalikan bukan dengan kekerasan, melainkan melalui kenikmatan dan kepuasan artifisial. Masyarakat diatur secara ketat dengan rekayasa genetika, pengkondisian sejak lahir, dan obat penenang bernama soma yang membuat orang selalu bahagia. Konsep seperti keluarga, cinta, dan seni dihapuskan demi stabilitas sosial. Tokoh utamanya, seperti Bernard Marx dan John “Si Liar” mencoba melawan sistem, tetapi pada akhirnya, masyarakat lebih memilih kepatuhan demi kenyamanan. Huxley memperingatkan bahwa bahaya terbesar bukanlah penindasan melalui kekerasan, melainkan ketidakpedulian manusia yang terbuai oleh hiburan dan kesenangan semu.
Perbedaan utama antara kedua novel ini terletak pada cara kontrol sosial dilakukan. Orwell menggambarkan kebebasan yang direnggut dengan paksa, sementara Huxley menunjukkan manusia justru dengan sukarela menyerahkan kebebasan mereka demi kenyamanan. 1984 menakutkan karena kekejamannya, sedangkan Brave New World justru menakutkan karena kenikmatannya yang palsu. Keduanya tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam membahas bahaya otoritarianisme, manipulasi media, dan hilangnya individualitas.
Bila Orwell takut pada mereka yang akan melarang buku, maka Huxley takut tidak ada alasan untuk melarang buku, karena tidak ada orang yang ingin membacanya. Bila Orwell takut pada mereka yang akan merampas informasi dari kita, maka Huxley takut pada mereka yang memberikan kita begitu banyak informasi sehingga kita akan menjadi pasif dan egois. Bila Orwell takut bahwa kebenaran akan disembunyikan dari kita, maka Huxley takut bahwa kebenaran akan tenggelam dalam lautan hal-hal yang tidak relevan. Dan bila Orwell takut kita akan menjadi budaya yang tertawan, maka Huxley takut kita akan menjadi budaya yang dangkal. Singkatnya, Orwell takut bahwa apa yang kita benci akan menghancurkan kita. Huxley takut bahwa apa yang kita cintai akan menghancurkan kita.
***
Di Indonesia saat ini, jika kita membandingkan dengan dua skenario dystopian dari Orwell dan Huxley, tampaknya situasi yang lebih mendekati adalah visi Huxleyan. Meskipun unsur Orwellian —- terkait dengan pengawasan, kontrol informasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi —- masih ada dalam bentuk-bentuk tertentu, terutama dalam beberapa regulasi terkait media, internet, dan kebijakan keamanan digital, kita melihat fenomena yang lebih dominan sesuai dengan ketakutan Huxley.
Salah satu elemen kunci dalam dunia Brave New World adalah masyarakat menjadi terlalu teralihkan perhatiannya oleh hiburan, kesenangan instan, dan hal-hal yang dangkal. Di Indonesia, dengan kehadiran teknologi digital, khususnya media sosial, platform hiburan seperti TikTok, YouTube, dan game online, banyak orang lebih terfokus pada konten-konten yang bersifat ringan, viral, dan kadang dangkal. Ini menciptakan budaya yang lebih terobsesi dengan hiburan dan hiburan cepat (fast entertainment), dan secara tidak sadar menurunkan kapasitas kritis dalam memahami isu-isu sosial, politik, dan budaya yang mendalam.
Selain itu, ketergantungan pada teknologi digital menciptakan apa yang disebut oleh Huxley sebagai “lautan hal-hal tidak relevan” (sea of irrelevance). Informasi berlimpah dan tersedia kapan saja, namun kualitasnya sering kali dipenuhi dengan konten yang bersifat hiburan semata. Akibatnya, informasi penting yang mungkin mengajak masyarakat berpikir kritis atau memahami situasi global lebih luas sering kali tenggelam dalam “noise” digital yang tidak relevan.
Dan seperti dalam visi Huxley — masyarakat dikendalikan melalui pemberian kesenangan, di Indonesia — banyak individu menjadi terikat pada kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi—seperti kemudahan belanja online, layanan hiburan streaming, hingga media sosial. Teknologi digital membuat masyarakat lebih nyaman dan terkadang terlalu puas dengan konsumsi digital sehingga tidak memperhatikan kebebasan yang mungkin berkurang atau isu-isu ketidakadilan lainnya.
Bagaimana dengan para pengkritik pemerintah yang ditarik masuk ke dalam dan diberikan jabatan strategis?
Silakan disimpulkan sendiri.